Minggu, 06 Mei 2012
PERTANIAN ORGANIK
LATAR BELAKANG
Rachel Carson (1962) pengarang buku
‘The Silent Spring’ (Musim Bunga) adalah orang yang pertama mengungkapkan
tentang dampak negative “dichloro diphenil trichlroothame” (DDT). DDT
adalah bahan aktif yang terkandung dalam pestisida kimia. Senyawa ini ditemukan
di Jerman pada tahun 1875 dan masuk ke Indonesia pada tahun 1950-an. Pemakaian
pestisida kimia paling gencar dilakukan oleh petani Indonesia awal tahun 1970
yaitu pada saat di mulainya gerakan revolusi hijau.
Revolusi hijau yaitu suatu sistem pertanian intensif (input luar tinggi)
yang selama ini diterapkan oleh sebagian besar petani di Indonesia harus di
akui telah dapat peningkatan produksi pertanian dan bahkan dengan sistem ini
Indonesia telah pernah mencapai swa sembada pangan. Akan tetapi disamping
keberhasilan tersebut, harus diakui pula bahwa ‘revolusi hijau’ telah memberi
dampak yang luar biasa terhadap lingkungan tanah, air, dan makhluk hidup
termasuk manusia. Revolusi hijau dengan cirri-ciri berupa penggunaan benih
hasil rekayasa genetik, pemakaian pupuk dan pestisida kimia. Ketiga komponen ini ternyata dapat memberi
pengaruh yang buruk terhadap lingkungan biotic dan abiotik, serta bagi produsen
dan konsumen produk-produk pertanian.
Adapun pengaruh buruk tersebut adalah :
- Ketergantungan.
- Pengaruh terhadap kesehatan
- Pengaruh terhadap lingkungan tanah, air dan udara.
a. Ketergantungan
Disadari atau tidak bahwa pemakai
input tinggi pada usahatani berupa saprodi yang terdiri dari benih unggul,
pupuk dan pestisida/hibrida kimia telah membuat ketergantungan luar biasa bagi
tani. Pada situasi ini petani seolah-olah tidak bedaya menjalankan usaha
taninya tanpa ada tersedianya saprodi tersebut.
Beberapa kearifan lokal (varietas dan budaya setempat ) menjadi punah.
Petani sangat berpengaruh terhadap ada tidaknya pasokan dari luar.
Demikian juga penggunaan pupuk dan
pestisida kimia telah menyebabkan hilangnya motivasi dan kemampuan petani dalam
penggunaan dan pembuatan pupuk atau pestisida alami, yang seterusnya tingkat
ketergantungan semakin parah. Ketergantungan terhadap input luar yang tinggi
ini juga telah menyebabkan terjadinya peningkatan biaya produksi yang harus
dikeluarkan oleh petani sebagai akibat tingginya harga benih unggul, pupuk dan
pestisida (herbisida kimia).
b. Pengaruh
Terhadap Kesehatan
Telah di ketahui bahwa adanya
pengaruh buruk pestisida terhadap pencetus timbulnya kanker, gangguan ginjal,
liver, tingkat kesuburan dan kesehatan reproduksi, gangguan paru-paru serta
sistem kekebalan tubuh. Bahan kimia yang
terkandung dalah pestisida/herbisida masuk ke dalam tubuh manusia melalui
hidung, mulut, dan kulit, yang selanjutnya akan berada dalam sistem tubuh
manusia. Masuknya senyawa-senyawa berbahaya kedalam tubuh manusia dapat terjadi
pada saat aplikasi pestisida atau melalui produk-produk pertanian yang memiliki
residu kimia berasal dari pestisida. Di
laporkan oleh WHO bahwa 14.000 orang meninggal dunia dan 750.000 keracunan
insektisida setiap tahun. Versi lain
menyebutkan bahwa setiap tahun terjadi lebih 400.000 kasus keracunan dan 1,5%
diantaranya fatal.
c. Pengaruh Terhadap Lingkungan
Tanah dan Air.
Beberapa
dampak negatif yang ditimbulkan oleh pemakaian pupuk dan pestisida/herbisida
kimia terhadap lingkungan adalah terjadinya degradasi tanah, polusi air dan
udara, serta rusaknya ekosistem fauna dan flora. Pemakaian pupuk an-organik dilaporkan telah
menyebabkan terjadinya pengerasan tanah (bantat) terutama karena pemakaian
urea. Pemakaian urea juga dapat menyebabkan kemasaman
tanah (terutama PH tanah). Disamping itu
pemggunaan pupuk dengan dosis tinggi telah timbulnya pahat/defisiasi beberapa
unsur hara di dalam tanah.
Sejak
akhir delapan puluhan telah terlihat adanya degradasi tanah dimana
produktivitasnya terjadi penurunan. Produksi tanaman mulai mandek yaitu tidak
lagi terjadi peningkatan walaupun telah digunakan pupuk, benih yang berasal
dari varietas unggul dan diikuti pula dengan pemeliharaan yang intensif dengan
berbagai paket usaha tani.
Aktivitas
pemakaian pestisida dan herbisida kimia juga telah menyebabkan terkontaminasi
tanah dan air. Beberapa biota tanah yang
berguna bagi tanaman dilaporkan mengalami kepunahan sehingga proses perombakan
daur ulang bahan organic terhenti/lambat.
Cacing tanah dan meso fauna lainnya sedikit berkembang di dalam tanah,
padahal diketahui binatang-binatang tersebut sangat berperan dalam peningkatan
kesuburan tanah.
Input
luar berupa pestisida/herbisida juga telah mematikan predator alami yang
berhubungan erat terhadap peningkatan populasi hama, gulma yang tahan (reristen)
Punahnya musuh alami dapat menyebabkan terjadi resurgensi species hama tertentu
yang berarti tingkat serangannya jauh lebih hebat dari sebelumnya. Kejadian ini ditimbulkan karena sifat
pestisida kimia yang memiliki tingkat keracunan di spectrum pengendalian luas
serta dapat mematikan organisme apa saja.
Berdasarkan
uraian sebelumnya, walaupun sistem pertanian dengan input luar tinggi di satu
sisi kelihatan menguntungkan, tetapi ternyata juga memiliki kerugian yang luar
biasa. Oleh karena itu solusi yang
dipandang tepat untuk tertanggunglanginya persoalan tersebut adalah dengan
penerapan pertanian organik.
PENGERTIAN PERTANIAN ORGANIK
Terdapat
beberapa pengertian dan definisi tentang pengertian organik, yaitu :
a. Menurut Fukuoka (1985), Pertanian Organik
diartikan sebagai praktek bertani secara alami, tanpa pupuk dan pestisida
buatan, sedikit mungkin mengolah tanah, namun hasilnya sama besar jelas
dibandingkan dengan pemakaian zat-zat kimia sintetik.
b. Sutanto
(2002), Pertanian Organik ditafsirkan sebagai suatu sistem produksi pertanian
yang berdasarkan daur ulang hara secara hayati.
c. Pertanian Organik diartikan pertanian ramah lingkungan yang merupakan
sistem pertanian yang tidak hanya meniadakan pupuk kimia buatan, pestisida kimia,
tetapi juga mengarah kepada sistem pertanian yang mempunyai visi kemerdekaan
dan kemandirian bagi petani, keselarasan alam dan kesehatan manusia (Ali Fahmi,
dkk), 2004).
Sedangkan
IFOAM (International Federation Of Organik Agriculture Movement) mendefinisikan
Pertanian Organik sebagai :
1.Memproduksi pangan dalam jumlah yang
mencukupi.
2.Mengupaya system budidaya alami
3.Mempertahankan siklus biologis
tanaman
4.Mengupayakan penggunaan sumber daya
yang dapat diperbaharui
5.Memungkinkan produsen memperoleh
pengembalian yang cukup dalam jangka panjang.
Beberapa macam pertanian organik,
antara lain biodinamika, regenatif dan natural. Biodinamika adalah sistem
pertanian yang cara penanaman berdasarkan waktu. Regeneratif adalah sistem pertanian disertai
dengan pengembalian ke dalam masukan-masukan yang berasal dari
biodinamika. Sedangkan natural adalah
sistem pertanian organik dengan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
tanah tidak diolah tidak ada penggunaan pupuk kimia, tidak dilakukan
pengendalian gulma dengan penggunaan herbisida dan tidak ada perlakuan
pemberian zat-zat kimia sebagai pengantar tumbuhan (Ali Fahmi, 2004).
Filosofi Pertanian Organik
Pertanian Organik adalah
mengembangkan prinsip-prinsip memberi makanan pada tanah yang selanjutnya tanah
menyediakan makanan untuk tanaman dan bukan memberi makanan langsung pada
tanaman (Sutanto, 2002).
Praktek pertanian berkelanjutan
secara filosofis pada dasarnya bersumber dari sistem atau model pertanian
tradisional yang telah lama dipraktekkan dan dipertahankan oleh petani.
Pertanian tradisional yang bersumber dan berkembang dari kearifan local dan
kearifan pengetahuan yang telah dipraktekkan oleh petani sejak ratusan tahun
yang lalu adalah sebuah tradisi yang menghargai, menjaga dan melindungi keberlanjutan
alam sebagai kehidupan (Ali Fahmi, dkk, 2004).
Konsep pertanian organik berawal
dari pemikiran bahwa hutan alam yang terdiri dari ribuan jenis tanaman bias
hidup subur tanpa campur tangan manusia. Kondisi hutan dapat memberi makanan
dan perlindungan dengan temperatur yang cocok untuk binatang besar ataupun
kecil, serangga, cendawan, bakteri dan makhluk hidup lainnya. Kotoran burung
atau binatang serta mulsa dauan-daunan secara perlahan, tetapi pasti akan
terurai sehingga menjadi makanan (pupuk) bagi tanaman (Pracaya, 2006).
PRINSIP PRINSIP PERTANIAN ORGANIK
Prinsip-prinsip ekologi dalam penerapan pertanian
organik dapat dipilahkan sebagai berikut :
- Memperbaiki kondisi tanah sehingga menguntungkan pertumbuhan tanaman, terutama pengelolaan bahan organik dan meningkatkan kehidupan biologi tanah.
- Optimalisasi ketersediaan dan keseimbangan daur hara, melalui fiksasi nitrogen, penyerapan hara, penambahan dan daur pupuk dari luar usaha tani.
- Membatasi kehilangan hasil panen akibat aliran panas, udara dan air dengan cara mengelola iklim mikro, pengelolaan air dan pencegahan erosi.
- Membatasi terjadinya kehilangan hasil panen akibat hama dan penyakit dengan melaksanakan usaha preventif melalui perlakuan yang aman.
- Pemamfaatan sumber genetika (plasma nutfah) yang saling mendukung dan bersifat sinergisme dengan cara mengkombinasikan fungsi keragaman sistem pertanaman terpadu.
PELUANG PERTANIAN ORGANIK DI INDONESIA
Letak dan iklim
Negara Indonesia yang terdiri
dari banyak kepulauan (lebih 13.000 bh) , yang membentang di antara benua,
beriklim tropis dengan ciri utama setiap tahun terdapat musim hujan dan musim
kemarau dengan tingkat keanekaragaman
hayati yang cukup tinggi, memungkinkan
banyak jenis tanaman tumbuh (1,3% dari permukaan dunia, 10% dihuni jenis
tumbuhan berbunga). Kondisi ini memberi kekuatan begitu besar alternatif bahan
pangan sehat (Sudiaty, 1998 dalam Sudaryanto, 2004).
Kekayaan budaya
Keanekaragaman kebudayaan yang
sangat membantu pelestarian lingkungan, seperti suku Baduy yang melarang menjual
hasil tani secara borongan, upacara keagamaan dengan menggunakan berbagai jenis
makanan terbuat dari ketan, adat istiadat yang memandang kurang sopan kalau
makan banyak dan kearifan tradisional seperti komunitas adat Kimaan yang
berhasil mengembangkan 144 kultivar ubi, komunitas adat “orang Dayak” di
Kalimantan yang berhasil mengatasi permasalahan lahan tidak subur (Nababan,
2001 dalam Sudaryanto, 2004).
Banyaknya angkatan tenaga kerja
Menurut Lukman Sutrisno, 1999
dalam Sudaryanto, 2004, sekitar 75% penduduk Indonesia tinggal di wilayah
pedesaan. Lebih dari 45% diantaranya menggantungkan hidup pada sektor
pertanian. Sebagian besar petani, yakni 40,73% berpendidikan SD, 4,62%
berpendidikan SLTA dan hanya 0,39% berpendidikan akademi/universitas sedang yang
47,33% tidak berpendidikan dan tidak tamat SD. Kondisi ini memungkinkan menjadi
masyarakat agraris yang cenderung padat karya.
Potensi Pasar
Pada tahun 2000, jumlah
penjualan produk pertanian organis di seluruh dunia mencapai $ 16 miliar dan
terus merangkak naik ke angka $ 23 miliar pada tahun 2003 dengan tingkat
pertumbuhan 5-20% per tahun dengan pasar terbesar adalah Eropa, USA, Kanada
& Jepang (Pranasari, 2004 dalam Sudaryanto, 2004), sedangkan di Indonesia
belum ada data pasti, survey yang dilakukan BIOCERT 2002-2003 terhadap 500
orang di 6 kota di Indonesia menunjukkan hal menggembirakan, 96% responden
mengenal PO dan terus ingin mengkonsumsi produk organis (Indro, 2004 dalam
Sudaryanto, 2004).
Hasil
penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan produksi tanaman budidaya
organik produk tanaman padi sawah yang dibudidayakan secara organik 5,44 ton
per hektar menjadi 9,733 ton per hektar.
TANTANGAN
- Belum ada contoh (demplot) PO yang sungguh ideal di tingkat basis (produsen/petani) di Indonesia.
Beberapa tempat masih
mengembangkan dari satu segi saja, umpama sayuran (BSB), padi (STPN, Kopi
(ACEH).
- Sumber daya manusia yang masih terbatas.
Perguruan tinggi sebagai
sumber para ahli belum mampu membuat kurikulum
untuk mencetak ahli PO, bali penelitian belum banyak yang berorientasi
pada aspek-aspek yang terkait dengan PO, pusat pengembangan PO masih terbatas.
- Sikap dan mentalitas pelaku PO
Petani modern sudah kehilangan
sikap tekun yang menjadi kunci dalam bertani organis, bahkan cenderung hanya
melihat satu segi pentingan bisnis belaka, termasuk para pengusaha juga.
ANALISIS SWOT
Adapun analisis SWOT (Strengths,
Weaknesess, Oportunity dan Threatness) untuk budidaya tanaman organik adalah
sebagai berikut :
Strengths (Kekuatan)
1. Potensi sumber daya alam melimpah
sehingga tersedia untuk bahan saprodi
2. Produk berkualitas dan
sehat sehingga aman untuk dikonsumsi
3. Teknis tersedia dan dapat dikuasai
dengan mudah oleh produsen/petani
4. Letak dan iklim mendukung
yang berarti dapat ditanami sepanjang tahun
5. Budaya cukup sesuai
kebiasaan masyarakat sangat mendukung
6. Tersedia sumber daya
manusia banyak penduduk yang terdapat di sentra
produksi/pedesaan.
7.Ramah
lingkungan yang berarti tidak mencemari tanah, air dan udara dan
aman bagi makhluk hidup lainnya.
Weaknesses (Kelemahan)
1. Asing bagi petani, sulit
diterima karena sudah terbiasa dengan sistem revolusi
hijau.
2. Terbatasnya lahan petani,
luasan kurang dari ½ ha setiap petani
3. Rendahnya akses pasar,
kurangnya data dan informasi yang tersedia
4. Terbatasnya pengetahuan,
sebagai akibat tidak adanya demplot dan
penyuluhan
5.Penampilan produk kurang
menarik, sebagai akibat bekas serangan penyakit
pada bahagian tanaman.
6.Adanya sertifikasi produk,
menyulitkan petani untuk pengurusannya.
7.Kemungkinan produksi
menurun.
Opportunity (Peluang)
1. Harga produk mahal yaitu
lebih tinggi dari pada produk yang konvensional
2. Terbuka peluang pasar,
sudah banyak permintaan di tingkat nasional dan
internasional.
3. Adanya dukungan para pihak,
mendapat sokongan dari pemerintah dan
swasta.
4. Adanya kebijakan yaitu
peraturan yang memungkinkan berkembangnya
pertanian organik.
5.Adanya bantuan teknologi
pemerintah, mulai disediakan paket-paket bantuan
saprodi maupun teknologi pertanian organik.
6.Permintaan kelas menengah meningkat, adanya
kecenderungan ini terutama di
kota-kota besar.
Threakness (Ancaman/Hambatan)
1. Tidak
ada kredit lunak, sehingga petani sulit berkembang karena kesulitan
modal
atau minim modal.
2. Ketergantungan
pada saprodi kimia menyebabkan petani tidak berdaya
3. Potensi
SDA terabaikan, banyaknya bahan-bahan baku saprodi yang tidak
termanfaatkan.
4. Persaingan
dengan produk konvensional, produk konvensional kelihatan
berpenampilan
bagus dan murah
5. Belum
terbukanya pasar lokal di beberapa daerah belum ada pasar khusus
produk
organik
6. Infrastruktur
tidak mendukung khusus bagi daerah bukaan baru belum
tersediaanya irigasi dan sarana angkutan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

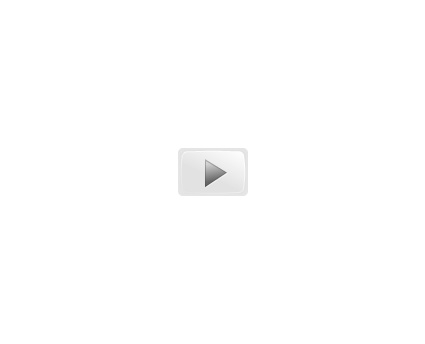
0 komentar:
Posting Komentar