Sabtu, 05 Mei 2012
Masalah resurgensi hama wereng paa tanaman padi yang terjaddi pada akhir
dekade 1970-an telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kemajuan
pembangunan pertanian di Indonesia.
Pengalaman ini mengajarkan bahwa pengendalian organisme pengganggu tanaman
(OPT) yang hanya mengandalkan pestisida sistesis akan berdampak buruk dimasa
yang akan dating, seperti resurgensi hama
dan pencemaran lingkungan.
Pada tahun 1986 pemerintah akhirnya menetapkan pengelolaan hama terpadu
(PHT) sebagai program nasional melalui Intruksi Presiden No. 3 tahun 1986 yang
merupakan upaya untuk mengantisipasi dampak buruk pemakaian pestisida sintesis.
Kebijakan ini di ikuti dengan pengurangan subsidi secara bertahap untuk
pestisida dan pada bulan Januari 1989 subsidi pestisida dihapuskan sama sekali.
PHT merupakan metode pengendalian serangan OPT dengan cara memanfaatkan
seluruh sumber daya yang tersedia untuk menekan populasi OPT hingga mencapai
taraf yang tidak merugikan. Setiap keputusan dan tindakan yang diambil dalam
bercocok tanam selalu bertujuan untuk meminimalisasi serangan OPT , sekaligus
merugikan bahaya yang ditimbulkan terhadap manusia, tanaman dan lingkungan.
Konsep PHT disusun berdasarkan prinsip keseimbangan ekosistem pertanian.
Hal-hal yang menjadi perhatian utama diantaranya hubungan antara tanaman dan
lingkungan fisik, seperti tanah dan kondisi iklim, hubungan antara OPT dan
tanaman, hubungan antara OPT dengan musuh alami, serta hubungan antara OPT dan
lingkungan fisik. Interelasi
tersebut akan sangat mempengaruhi penyusunan program PHT di lapangan.
Keberhasilan pelaksanaan PHT
sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia yang mengelola pertanian.
Karenanya, Departemen Pertanian telah menyediakan Sekolah Lapangan Pengelolaan
Hama terpadu (SLPHT) untuk para petani. Pengetahuan para pengelolaan pertanian
tentang OPT, seperti gejala awal serangan hama dan penyakit, identifikasi
jenis-jenis OPT yang spesifik, siklus hidup OPT dan bangaimana interaksinya
dengan lingkungan fisik, merupakan kunci keberhasilan penerapan PHT. Sebagai
contoh, musim panas yang panjang akan
menyebabkan perkembangan serangga lebih cepat, sedangkan pada musim
hujan serangan penyakit jamur dan bakteri akan meningkat. Dari pengetahuan dasar tersebut dapat ditentukan
waktu dan tindakan yang harus dilakukan.
Pada pemakaian pestisida
alami, pengetahuan siklus hidup OPT menjadi sangat penting. Pestisida alami
cepat terurai sehingga sifat racunnya sangat cepat hilang. Hal ini menuntut
ketetapan waktu penyemprotan yang tinggi. Sebagai contoh pemakaian bakteri bacillus thuringiensis lebih efektif
untuk mengendalikan serangan pada tahap larva.
Pelaksanaan PHT bias dikatakan
berhasil jika populasi OPT dapat dikendalikan, sehingga secara ekonomi tidak
merugikan, diikuti dengan peningkatan hasil panen dan biaya produksi yang
bermuara pada peningkatan pendapatan petani. Sementara itu, dampak buruk pengendalian hama
terhadap manusia dan lingkungan diperkecil.
A. Tindakan Pencegahan
Penerapan PHT lebih menekankan kepada tindakan yang
bersifat pencegahan dan mengetumakan pertumbuhan tanaman yang sehat. Karenanya, PHT tidak akan berhasil tanpa
program budi daya yang baik dan benar. Tanaman yang sehat terntunya akan lebih
tahan terhadap serangan OPT dan lebih cepat sembuh setelah terjadi serangan
hama dan penyakit. Praktik budi daya yang dilakukan di lapangan akan
mempengaruhi keberadaan suatu penyakit atau hama tertentu dan berpengaruh pula
terhadap besar kecil tingkat serangan. Misalnya, pemakaian nitrogen sampai
batsa tertentu akan meningkatkan pertumbuhan tanaman. Peningkatan pupuk
nitrogen ini jika tidak diikuti dengan aspek budi daya lainnya akan mempengaruh
buruk, karena akan meningkatkan pengambilan air. Jika peningkatan kebutuhan air
tidak dapat terpenuhi, akan menyebabkan tanaman stress dan mudah terserang
penyakit.
B. Tindakan Pengendalian
Dalam program PHT, tindakan pengendali OPT baru
dilakukan jika jumlah populasi OPT yang ditemukan di lapangan telah melewati
batas toleransi. Batas toleransi ini biasanya disebut sebagai nilai ambang
ekonomi. Petani dan praktisi pertanian dapat menetapkan sendiri nilai ambang
ekonomi untuk setiap jenis tanaman yang diusahakan berdasarkan pengalaman
masing-masing. Nilai ambang ekonomi seperti tercantum pada Tabel 2 menunjukkan
jumlah maksimum dari jenis OPT tertentu yang masih dapat diterima dan tidak
perlu dikendalikan, karena belum menimbulkan kerusakan dan kerugian yang
berarti. Jika populasi OPT telah melewati nilai ambang ekonomi, kerugian yang
akan ditimbulkan akibat serangan OPT akan lebih besar dibandingkan dengan biaya
pengendaliannya, sehingga secara ekonomi tindakan pengendalian sudah layak
dilakukan.
a.
Perlakuan Fisik
Perlakuan atau tindakan fisik lebih banyak dilakukan
untuk mengendalikan serangan hama. Contohnya
: Pemangkasan, pengumpulan hama, pemakaian perangkap dan pemasangan
orang-orangan.
b.
Pengandalian Biologis
Pengendalian biologis ini dilakukan dengan menyebarkan
dan memelihara musuh alami atau predator dari OPT tertentu di daerah pertanian.
c.
Pengendalian Kimiawi
Program PHT masih mengizinkan pemakaian racun kimia
buatan (pestisida sintesis) untuk mengendalikan OPT, asal dilakukan dengan
metode yang benar.
C. Peranan Pestisida Alami
Pemakaian pestisida alami dan penerapan PHT adalah dua
hal yang saling mendukung. Penerapan PHT bertujuan untuk menekan dampak
negative pemakaian pestisida sintesis, mencegah resurgensi dan kekebalan OPT,
serta memanfaatkan semaksimal mungkin kemampuan alam untuk mengendalikan OPT,
hal ini sangat sejalan dengan tujuan pemakaian pestisida nabati yang ramah
lingkungan.
Program PHT sangat menginginkan jenis pestisida yang
dapat megendalikan perkembangan OPT dengan efektif, bersifat selektif (hanya
mematika OPT tertentu) dan tidak membahayakan kehidupan musuh alami, serta
dapat terurai dengan cepat oleh faktor-faktor alam. Pestisida nabati cepat
terurai oleh faktor-faktor lingkungan hasil penguraiannya akan kemabali kea lam
dalam bentuk bahan yang tidak mengandung racun. Berbeda halnya dengan pestisida
sintesis yang telah berada didalam tanah dan air dalam bentuk senyawa beracun
hingga bertahun-tahun.
Persyaratan pertisida ideal yang diinginkan pleh
program PHT ini seluruhnya dapat dipenuhi oleh berbagai macam pertisida nabati.
Pemakaian pertisida nabati memanga akan sangat mendukung keberhasilan PHT, tetapi
pemakaian pertisida hanya merupakan satu dari sekian banyak faktor yang harus
mendapat perhatian untuk keberhasilan PHT. Tanpa memperhatikan
konponen-konponen PHT lainnya, pemakaian pestisida nabati juga berpotensi
menyebabkan kekebalan dan resurgensi OPT.
Sifat pertisida nabati yang cepat terurai ini di sisi
lain merupakan kelemahan, karena pestisida nabati tidak mampu terlalu lama
menjaga tanaman dari gangguan OPT,
sehingga menuntut cara aplikasi yang lebih spesifik. Pemakaian pestisida nabati
dalam mengendalikan OPT tidak akan memberikan hasil yang optimal tanpa diikuti
penerapan sistem PHT. Tingkat keberhasilan pengendalian hama dengan pestisida
nabati akan sangat rendah jika komponen-komponen lain dalam PHT tidak mendapat
perhatian. Sebaliknya tingkat keberhasilan pestisida nabati bisa lebih tinggi
dibandingkan dengan pestisida sintesis jika dilakukan dalam kerangka PHT.
Pemakaian pestisida nabati yang intensif telah
melahirkan konsep baru yang merupakan pengembangan dari PHT dan dikenal sebagai
alternate pest management
(pengelolaan hama alternatif). Konsep yang terakhir ini umumnya diterapkan pada
sistem pertanian organik yang sama sekali tidak memakai pestisida sintesis.
Pestisida nabati ramah lingkungan ini juga dapat menyebabkan kekebalan hama dan
resurgensi hama
jika faktor-faktor lain dalam PHT mulai ditingkatkan.
D. Fungsi dan Kelebihan Pestisida Nabati
Pestisida nabati memiliki sejarah panjang dan telah
menjadi tradisi bangsa-bangsa didunia. Bangsa Romawi kuno telah memiliki minyak
zaitun sebagai pestisida. Mamba telah lama dipakai di India dan sekarang India
telah menjadi produsen pestisida nabati dengan bahan aktif mamba. Akar tuba
dilaporkan telah dipakai di Malaysia sejak pertengahan tahun 1800, dan piretrum
dipakai di Persia (Iran) sejak tahun 1800-an. Tembakau memiliki sejarah yang
lebih tua, bangsa prancis telah memakainya sebagai insektisida sejak tahun
1600-an.
Penelitian tentang tanaman-tanaman beracun nabati di
Indonesia dimulai sejak didirikannya Pusat Ilmu Pengetahuan Botani oleh belanda
pada tahun 1888. sementara itu, penelitian tentang pemanfaatan tanaman tuba (Derris sp.), bunga krisan liar (Pyrethrum), dan bengkuang sebagai
pestisida nabati dimulai sejak dekade 1950-an. Saat ini setidaknya terdapat
lebih dari 2.000 jenis tanaman yang telah dikenal memilikikemampuan sebagai
pestisida. Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (Balitron) di Bogor
memiliki koleksi puluhan jenis tanaman yang dapat dipakai sebagai insektisida.
Secara alami tanaman memproduksi senyawa beracun untuk
melindungi spesiesnya dari kepunahan akibat serangan hama dan penyakit.
Senyawa-senyawa ini disebut metabolit sekunder. Spesies tanaman yang tidak
pernah diserang OPT yang menjadi pengganggu tanaman lain bisa jadi mengandung
bahan metabolit sekunder yang dapat dipakai sebagai pestisida.
E. Mengenal Pestisida Nabati
Untuk menghadapi berbagai macam tantangan pembungan
pertanian, pemerintah beserta masyarakat harus mampu membuat
terobosan-terobosan dengan berbagai alternatif yang dapat memberikan jalan
keluar dari permasalahan dengan tidak melupakan kepedulian terhadap lingkungan
dan mengutamankan keberpihakan kepada petani. Suatu alternatif pengendalian
hama penyakit yang murah, praktis, dan relatif aman terhadap lingkungan sangat
diperlukan oleh negara berkembang seperti Indonesia dengan kondisi petaninya
yang memiliki modal terbatas untuk membeli pestisida sintesis. Masalah produksi
pertanian, khususnya produksi pangan, menjadi masalah yang sangat delematis. Di
satu sisi penggunaan pestisida, khususnya pestisida sintesis sangat membantu
peningkatan produktivitas hasil pertanian, walaupun telah disadari pula dampak
negatif yang ditimbulkan tidak kecil.
Namun demikian, apabila penggunaan pestisida sintesis dihentikan secara drastis
maka dikhawatirkan produksi pertanian akan turun. Oleh karena itu, sudah tiba
saatnya untuk memasyarakatkan pestisida nabati yang ramah lingkungan.
Secara umum, pestisida nabati diartikan suatu
pestisida yang bahan dasarnya berasal dari tumbuhan. Pestisida nabati relatif
mudah dibuat dengan kemampuan dan pengetahuan tang terbatas. Oleh karena
terbuat dari bahan alami/nabati maka jenis pestisida ini bersifat mudah terurai
(biodegradable) di alam sehingga
tidak mencemari lingkungan dan relatif aman bagi manusia dan ternak peliharaan
karena residunya mudah hilang. Pestisida nabati bersifat “pukul dan lari” (hit and run), yaitu apabila
diaplikasikan akan membunuh hama
pada waktu itu dan setelah hamanya terbunuh maka residunya akan cepat
menghilang di alam. Dengan demikian,
tanaman akan terbebas dari residu pestisida dan aman untuk di konsumsi. Penggunaan
pestisida nabati dimaksudkan buka untuk meninggalkan dan menganggap tabu
penggunaan pestisida sintesis, tetapi hanya merupakan suatu cara alternatif
dengan tujuan agar pengguna tidak hanya tergantung kepada pestisida sintesis.
Tujuan lainnya adalah agar penggunaan pestisida sintesis dapat diminimalkan
sehingga kerusakan lingkungan yang diakibatkannya pun diharapkan dapat
dikurangi pula.
Secara
evolusi, tumbuhan telah mengembangkan bahan kimia sebagai alat pertanahan alami
terhadap pengganggunya. Tumbuhan mengandung banyak bahan kimia yang merupakan
produksi metabolistik sekunder dan dugunakan oleh tumbuhan sebagai alat
pertahanan dari serangan organisme pengganggu. Tumbuhan sebenarnya kaya akan
bahan bioaktif. Walaupun hanya sekitar 10.000 jenis produksi metabolit sekunder
yang telah terindektifikasi, tetapi jumlah bahan kimia pada tumbuhan dapat
melampaui 400.000. lebih dari 2.400 jenis tumbuhan yang termasuk ke dalam 235
famili dilaporkan mengandung bahan pestisida. Oleh karena itu, apabila kita
dapat mengolah tumbuhan ini sebagai bahan pestisida maka akan sangat membantu
masyarakat petani kita untuk mengembangkan pengendalian yang ramah lingkungan
dengan memanfaatkan sumber daya setempat yan terdapat disekitarny.
BAB II.
PEMBUATAN PESTISIDA NABATI
Cara pembuatan pestisida
nabati dari berbagai jenis tumbuhan tidak dapat dijelaskan secara khusus atau
distandarisasi karena memang sifatnya tidak berlaku umum. Suatu ramuan pestisida
nabati yang berhasil baik atau bersifat efektif di suatu tempat belum tentu
berhasil dengan baik pula ditemapat lainnya karena ramuan pestisida nabati
bersifat site specific (khusus
lokal). Salah satu penyebabnya adalah pada tumbuhan yang sama, tetapi jika
tumbuh di lingkungan yang berbeda maka kandungan bahan aktifnya pun dapat
berbeda pula. Oleh karena, dosis atau konsentrasi bahan aktif yang digunakannya
pun akan berbeda pula. Berkaitan dengan masalah ini maka ramuan pestisida
nabati akan tergantung kepada hasil pengujian di lokasi setempat dan mungkin
tidak akan berlaku ditempat lain ( tidak
berlaku umum).
Secara garis besar pembuatan
pestisida nabati dibagi menjadi dua cara, yaitu secara sederhana dan secara
laboratorium. Cara sederhana (jangka pendek) dapat dilakukan oleh petani dan
penggunaan ekstrak biasanya dilakukan sesegera mungkin setelah pembuatan
ekstrak dilakukan. Cara laboratorium membutuhkan alat dan bahan kimia khusus
serta harus dilakukan tenaga ahli. Hal tersebut menyebabkan produk pestisida
nabati menjadi mahal, bahkan sering kali lebih mahal dari pada pestisida
sintesis yang sekarang sudah banyak beredar. Selain biaya yang mahal, proses
pembuatan cara laboratorium memerlukan penanganan khusus, seperti penyimpanan
yang khusus karena sifat pestisida nabati mudah terdegradasi. Oleh karena itu,
pembuatan dan penggunaan pestisida nabati lebih diarahkan dan dianjurkan kepada
cara sederhana, untuk luasan terbatas, dan dalam jangka waktu penyimpanan
terbatas (biasanya langsung pakai). Namun, lain halnya apabila penggunaannya
diarahkan kepada kegiatan organic farming (pertanian organik) yang
menghindar penggunaan bahan-bahan kimia sintesis, bisa jadi harga yang mahal
tidak menjadi masalah karena produk organic
farming memang relatif mahal.
Untuk menghasilakn bahan
pestisida nabati dapat dialakukan beberapa teknik berikut :
a) Penggerusan, penumbukan, pembakaran, atau
pengepresan untuk menghasilkan produk berupa tepung, abu, atau pasta.
b) Rendaman untuk produk ekstrak.
c) Ekstraksi dengan menggunakan bahan kimia
pelarut disertai perlakuan khusus oleh tenaga yang terampil dan dengan
peralatan yang khusus.
Dengan dikembangkannya
pemanfaata pestisida nabati diharapkan petani atau pengguna dapat mempersiapkan
sendiri cara pengendalian hama terpadu.
BAB III. KENDALA DAN PELUANG
PENGGUNAAN
PESTISIDA NABATI
Di Indoneisa, penggunaan
pestida nabati masih belum memasyarakat. Hal ini berkaitan dengan bebrapa
kendala yang dihadapi dalam penggunaannya. Dengan mengetahui kendala-kendala
penggunaannya maka diharapkan akan muncul jalan keluar dari masalah tersebut
sehingga peluang penggunaannya pun semakin terbuka lebar.
A.
Kendala Penggunaan Pestisida Nabati
Bekaitan dengan beberapa
manfat yang didapatkan dari pestisida nabati maka sudah selayaknya jika
penggunaan jenis pestisida ini harus dimasyarakatkan. Namun demikian,
penggunaan dan pengembangan pestisida nabati di Indonesia mengalami beberapa
kenadala berikut.
a. Pestisida sintesis tetap lebih disukai
dengan alasan mudah didapat, praktis mengaplikasikannya, hasilnya relatif cepat
terlihat, tidak perlu membuat sediaan sendiri, tersedia dalam jumlah banyak,
dan tidak perlu membudidayakan sendiri tanaman penghasil pestisida.
b. Kurangnya rekomendasi atau dorongan dari
pengambil kebijakan (lack of official
recommendation). Hal ini terlihat dari kurangnya atau tidak adanya penyuluh
dan pengenalan penggunaan pestisida nabati kepada petani atau pengguna. Hal ini
mungkin terjadi karena keterbatasan pengetahuan para penyuluh atau petugas
pertanian terkait dengan pestisida nabati.
c. Tidak tersedianya bahan secara
berkesinambungandalam jumlah yang memadai saat diperlukan.
d. Walau penggunaan pestisida nabati
menimbulkan residu relatif rendah pada bahan makanan dan lingkungan serta
dianggap lebih aman dari pada pestisida sintesis, tetapi frekwensi penggunaan
menjadi tinggi. Tingginya frekwensi penggunaan jenis pestisida ini karena
sifatnya yang mudah terurai di alam sehingga memerluka pengaplikasian yang
lebih sering.
e. Sulitnya regristrasi pestisida nabati
mengingat pada umumnya jenis pestisida ini memiliki bahan aktif yang komplek (multiple active ingredient) dan pada
beberapa kasus tidak semua bahan aktif dapat dideteksi. Di lain pihak, apabila
teradapat pestisida nabati hanya terdiri diri satu bahan aktif maka sifatnya
tidak berbeda dengan pestisida sintesis, yaitu umumnya sering membuat hama
menjadi resisten terhadap bahan ini. Sebagai contoh, untuk registrasi pestisida
nabati Margosan-O di Amerika yang dilaporkan hanya mengandung azadirachtin
(berasal dari tanaman mimba) menghabiskan dana sekitar $100.000 atau sekitar
Rp. 800.000.000.
Selain kendala-kendala di
atas, pada tanaman pestisida nabati yang sama, tetapi tumbuh ditempat yang
berbeda, umur tanaman berbeda, iklim berbeda, jenis tanah berbeda, ketinggian
temp[at berbeda, dan waktu panen yang berbeda menyebabkan kandungan bahan
aktifnya menjadi sangat berfariasi. Hal ini mengakibatkan perlunya dilakukan
suatu penelitian khusus lokasi (site
spesific) di daerah yang akan menggunakan pestisida nabati atau di buat dalam
suatu kemasan atau formula dengan kadar bahan aktif tertentu. Untuk cara yang
kedua tentunya diperlukan alat, tenaga, dan biaya tersendiri. Oleh karena itu,
sangat diperlukan bimbingan dari petugas lapangan untuk sekedar uji coba
mengebai perbandingan tanaman dengan pelarut atau tentang konsentrasi dan dosis
yang sesuai di suatu tempat.
B.
Peluang Penggunaan Pestisida Nabati
Pada tahun 1960 negara-negara
industri bersepakat untuk membentuk Organization Economic Corporation
Development (OECD). Akhir-akhir ini OECD melakukan evaluasi tentang
perkembangan organic farming (pertanian organic) yang pertama
dikembangkan pada tahun 1993 di masing-masing negara anggota OECD. Disamping
pertanian organik, dipakai istilah-istilah seperti law input agricurture,
alternatife agriculture, dan subtainable
agricultire (LISA). Walaupu istilah yang digunakan bermacam-macam, tetapi
pada prinsipnya sistem pertanian di atas adalah sama. Kesamaan tersebut dapat
dilihat pada kriteria berikut.
a. Menghasilkan produk pertanian dengan kualitas
dan kuantitas yang optimal.
b. Bersahabat dengan alam.
c. Mengupayakan kesuburan tanah secara
lestari.
d. Meminimalkan kemungkinan terjadinya
kerusakan lingkungan hidup.
e. Meminimalkan pemakaian bahan yang tidak
dapat diperbaharui.
Penerapan sistem pertanian organik
yang dilakukan oleh negara-negara yang tergabung dalam OECD menunjukkan bahwa
subsidi pemerintah tidak berupa sarana penelitian, tetapi berupa latihan bagi
petani dan petugas pertanian serta memicu kegiatan penelitian. Dengan
mengadakan latihan secara intensif diharapkan dapat meningkatkan sumber daya
manusia. Di Indonesia, akhir-akhir ini telah mulai banyak kegiatan-kegiatan
petani dengan sistem pertanian organik tanpa menggunakan pestisida sintesis,
tetapi menggunakan pestisida nabati.
Indonesia terkenal kaya akan
keanekaragaman hayati, termasuk jenis tumbuhan yang mengandung bahan aktif
pestisida. Sebenarnya sejak dahulu penduduk Indonesia sudah menggunakan
tumbuh-tumbuhan tersebut sebagai racun serangga atau racun ikan. Seandaiannya
kebutuhan pestisida sintesis di Indonesia saat ini mencapai 20.000 ton dengan
nila sekitar 200 – 300 miliar rupiah per tahun dapat diisi oleh pestisida
nabati sebesar 10% saja maka devisa yang dapat dihemat mencapai 20 – 30 miliar
rupiah per tahun. Keuntungan lain yang diperoleh dari penggunaan pestisida
nabati adalah akan meningkatkan perkembangan agroindustri, khususnya industri
pedesaan, pertumbuhan usaha baru dan kelestarian lingkungan.
Dengan melihat kekayaan
keanekaragaman hayati di Indonesia, keadaan sosial ekonomi sebagian besar
petani Indonesia, program internasional mengenai kegiatan pertanian organik
yang sangat mendukung penggunaan pestisida nabati, peraturan pendaftaran
pestisida nabati di Indonesia yang relatif sederhana (khususnya yang digunakan
sendiri), hasil-hasil penelitian dan teknologi sederhana yang tersedia, serta
hal-hal lainnya yang mendukung maka peluang penggunaan pestisida nabati di
Indonesia terbuka cukup lebar.
BAB IV.
BAHAYA TUMBUHAN INSIKTISIDA NABATI.
1.
Bengkuang bagian yang digunakan biji
2.
Bitung bagian
yang digunakan biji
3.
Jerigen bagian
yang digunakan rimpang
4.
Saga bagian
yang digunakan biji
5.
Sirai
bagian
yang digunakan daun dan batang
6.
Sirsak bagian
yang digunakan daun dan biji
7.
Srikaya bagian
yang digunakan daun dan biji
8.
Tuba Rasa bagian yang digunakan daun dan biji
9.
Kamala Kain bagian yang digunakan biji
10. Suren
bagian yang
digunakan daun
11. Mimba
bagian yang
digunakan biji, daun dan ranting
12. Bawang
putih bagian yang
digunakan umbi
13. Mahoni
bagian yang
digunakan biji
14. Lada
bagian yang
digunakan biji
15. Kemuning
bagian yang
digunakan batang dan ranting
16. Tembakau
bagian yang
digunakan daun dan batang
17. Sirih
bagian
yang digunakan daun
18. Cengkeh
bagian yang
digunakan daun dan batang
19. Bawang
merah bagian yang digunakan
umbi
20. Cabe
Merah bagian yang
digunakan buah
21. Lengkuas
bagian yang
digunakan batang
22. Gadung
bagian yang
digunakan umbi
23. Kunyit
bagian yang
digunakan umbi
24. Tuba
jieen bagian yang
digunakan akar
25. Jambu
mede bagian yang
digunakan kulit buah
26. Jarah
bagian yang
digunakan semua bagian tanaman
27. Kembang
(truf payo) bagian yang digunakan daun dan biji
28. Sintang
bagian yang
digunakan daun
29. Capa bagian yang
digunakan daun
30.
Bak lakom bagian yang digunakan batang dan daun
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


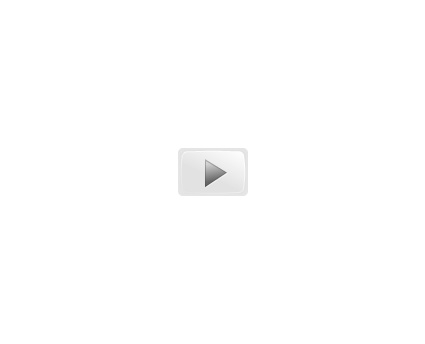
0 komentar:
Posting Komentar